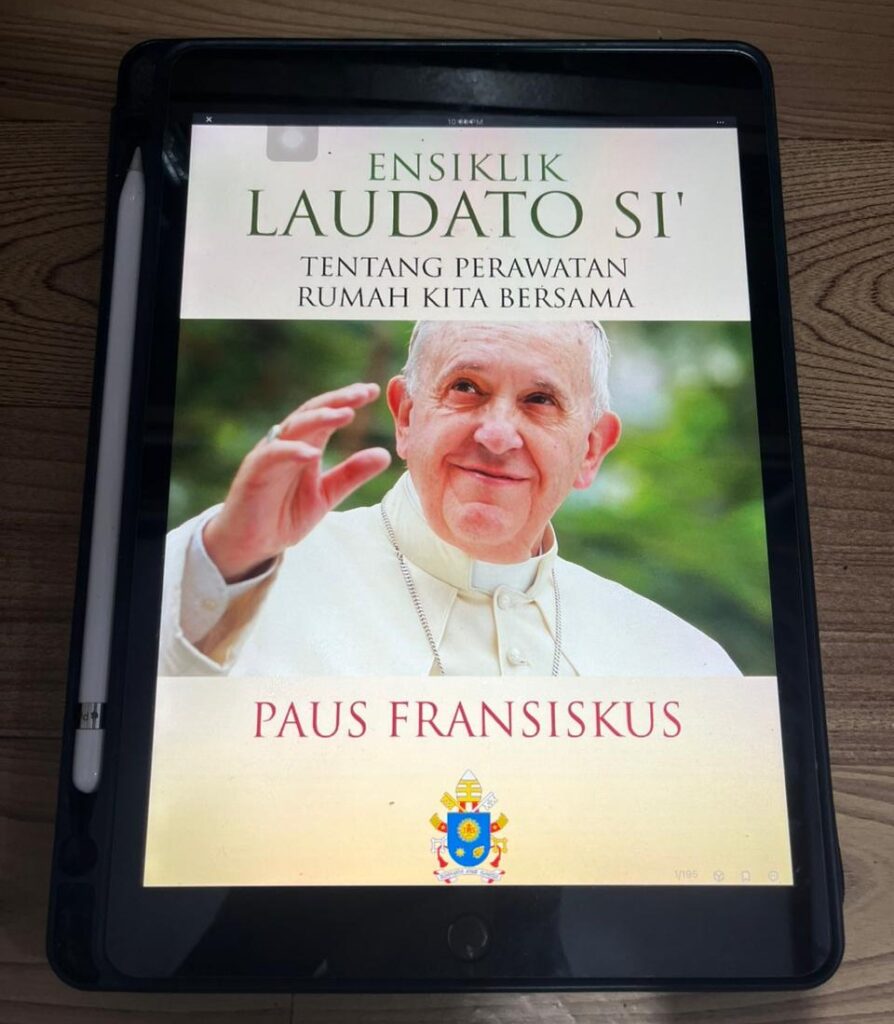
Laudato Si’: On the Care for Our Common Home (Tentang Perawatan Rumah Kita Bersama) merupakan ensiklik kedua yang dikeluarkan Paus Fransiskus pada Tahun 2015. Ensiklik ini ditujukan kepada semua orang di dunia ini yang peduli pada isu-isu lingkungan.
Kehadiran ensiklik ini menjadi bahan perbincangan karena Paus Fransiskus merupakan pimpinan gereja katolik pertama yang mengeluarkan ensiklik yang berfokus pada isu lingkungan. Isi dokumen Laudato Si’ mudah dipahami karena menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Seruan-seruan moral dan kesusilaan yang disampaikan berlandaskan pada fakta-fakta saintifik terbaik dan tersedia dan refleksi-refleksi para teolog terkait hal itu. Kolabarasi ilmuan dan teologi membuat dokumen ini amat menarik karena relevansinya dengan isu-isu kompleks yang dihadapi manusia dan bagaimana orang beriman perlu memaknai peran-peran untuk perawatan bumi.
TTulisan ini adalah bagian kedua dari ulasan dan refleksi personal saya terkait dokumen Laudato Si’. Di tulisan sebelumnya, saya sempat menyinggung, muatan ensiklik yang terdiri dari enam bab;
- Apa yang Terjadi dengan Rumah Kita
- Kabar Baik Penciptaan
- Akar Manusiawi Krisis Ekologis
- Ekologi Integral
- Beberapa Pedoman untuk Orientasi dan Aksi
- Pendidikan dan Spiritualitas Ekologi
Setiap bab terdiri dari beberapa bagian yang mengulas secara khusus isu-isu atau aspek-aspek tertentu. Saya akan meringkas beberapa bagian yang saya temukan menarik pada setiap bab.
Bab 1: Apa Yang Terjadi Dengan Rumah Kita?
Bab ini dibuka dengan ajakan untuk melihat kondisi rumah kita, bumi yang kita huni. Pemahaman kita tentang kondisi bumi yang sedang buruk diharapkan dapat mendorong kepedulian kita untuk ikut berkontribusi dalam merawatnya.
Ajakan ini menjadi relevan dengan pembahasan tentang isu-isu polusi dan degradasi lingkungan, krisis air, dan perubahan iklim. Isu-isu ini punya efek domino pada kesejahteraan dan keberlangsungan hidup manusia. Keterkaitan ini disampaikan dengan bahasa yang sangat sederhana dan mudah dipahami.
Saya sangat antusias membaca bab ini apalagi polusi visual dan kebisingan ikut dibahas. Dua isu ini relatif kurang populer dibandingkan isu-isu pencemaran udara dan pencemaran air, sehingga seringkali kurang kita perhatikan. Polusi cahaya dan polusi suara sebenarnya berdampak pada kenyamanan dan kesehatan manusia, serta eksistensi keanekaragaman hayati yang kita miliki.
Isu-isu lingkungan juga dikaitkan dengan budaya sekali pakai yang punya konsekuensi pada meningkatnya timbulan sampah. Bagian ini juga memuat kritik terhadap kegiatan ekonomi dan politik kita yang cenderung mengabaikan dampak-dampak perubahan iklim pada kesejahteraan manusia.
Bab awal ini kemudian ditutup dengan penegasan bahwa bumi sementara menderita dan membutuhkan respon kita. Kehidupan manusia berubah seturut jaman. Bumi pun ikut berubah. Sayangnya, kita cenderung berpikir kondisi bumi statis tanpa perubahan apapun, sehingga kita belum bisa mengembangankan suatu pola respon yang sesuai dengan situasi bumi yang sudah jauh berbeda dari yang kita bayangkan.
Meski begitu, bab ini juga mengakui adanya keragaman pandangan manusia tentang situasi sekarang dan bagaimana menangani krisis. Sehingga perlu ada dialog untuk menemukan jalan keluar yang sesuai.
Bab 2: Kabar Baik Penciptaan
Bab kedua Laudato Si’ terfokus pada keyakinan iman kristen, sehingga ada banyak tinjauan teologis yang dibahas disini. Bab ini dipandang relevan dalam pembahasan isu-isu lingkungan karena kita perlu menimbang berbagai pendekatan ketika berdialog untuk mencari solusi bagi persoalan-persoalan lingkungan. “Maka tidak ada cabang ilmu dan tidak ada jenis kebijaksanaan yang dapat diabaikan.” (Laudato Si’ paragraf 63).
Meskipun pendekatan agama berbeda dengan ilmu pengetahuan, namun ajaran agama menawar berbagai kebijaksanaan yang bisa membantu kita merefleksikan eksistensi kehidupan manusia di bumi. Terlepas dari keberiman, kita semua meyakini, bumi adalah rumah kita bersama. Tanggung jawab untuk memelihara bumi juga diajarkan dalam Alkitab.
Bagi saya bab ini agak nostalgik karena mengingatkan saya pada bapa saya. Ia selalu memakai kisah-kisah penciptaan untuk memaknai relasi-relasi dan tanggung jawab manusia di bumi. Bab ini juga mengingatkan saya pada kuliah-kuliah ilmu lingkungan yang membahas tentang perlunya membangun harmonisasi hubungan manusia dengan alam dan intervensi-intervensi manusia terhadap regulasi alam yang menimbulkan konsekuensi-konsekuensi negatif yang merugikan manusia.
Secara umum, kita akan menjumpai cerita-cerita Alkitab yang penuh hikmat dari kisah-kisah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
Kisah penciptaan dalam Perjanjian lama mengingatkan kita kembali pada tiga relasi dasar yang berhubungan dengan eksistensi manusia; relasi dengan Tuhan, sesama, dan bumi. Namun, manusia cenderung memusatkan segala sesuatu pada dirinya sendiri dan merusak keharmonisan dalam relasi tersebut.
Kita juga diingatkan pada adanya waktu istirahat (sabat), yang tidak hanya diperuntukan bagi manusia saja tetapi juga alam dan makhluk hidup lain. Namun terkadang kita lupa bahwa alam adalah milik semua orang, sehingga kita menjadi serakah. Akibatnya hubungan kita dengan Tuhan, alam, dan sesama manusia menjadi tidak harmonis.
Manusia diberkati dengan akal budi untuk bisa hidup dengan bermartabat; mampu memelihara bumi dan menghormati ciptaan Tuhan. Karena itu, pemulihan pada hubungan-hubungan yang tak harmonis mencakup penemuan kembali pada penghormatan terhadap irama sang Pencipta yang terwujud dalam alam. Selanjutnya di bagian-bagian akhir bab ini, kita diajak melihat pada Yesus dalam kisah-kisah Perjanjian Baru, yang hidup dalam harmoni dengan dunia dan manusia.
Bab 3: Akar Manusiawi Krisis Ekologis
“Terdapat suatu cara memahami hidup dan aktivitas manusia yang keliru dan bertentangan dengan realitas dunia hingga merugikan. Mengapa kita tidak berhenti sejenak untuk memikirkannya?”
Laudato Si’: on the Care for Our Common Home, paragraf 101
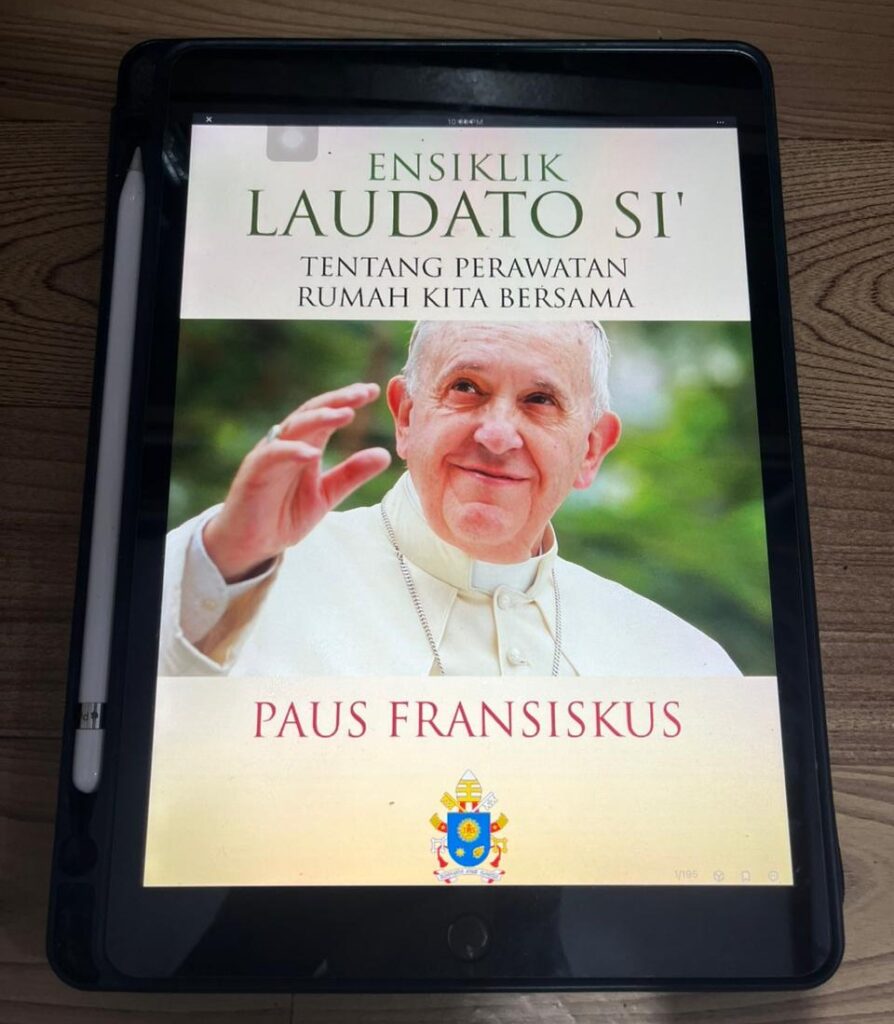
Ada dua hal penting yang dibahas dalam bab ini, paradigma teknokratis dan antroposisme modern. Dua hal ini masih paralel dengan apa yang dibahas pada bab sebelumnya. Disini, kita beralih dari konsep-konsep biblis ke realita-realita kehidupan kita dalam bingkai ketakharmonisan dengan alam dan ciptaan Tuhan lainnya.
Menarik, bagian awal bab ini bicara tentang teknologi yang memungkinkan revolusi dan perubahan jaman. Teknologi adalah buah dari kreativitas manusia yang memungkinkan beragam transformasi kehidupan yang lebih baik. Namun di sisi lain, penguasaan teknologi juga membuat kita terpesona pada kekuasaan, sehingga memungkinkan penerapan teknologi yang berbahaya bagi alam dan makhluk hidup lainnya.
Bagian ini kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terkait globalisasi paradigma teknokratis yang mendominasi kehidupan manusia; sosial, ekonomi, dan politik. Paradigma teknokratis membuat kita tidak melihat sesuatu secara utuh, sehingga kita kehilangan kepekaan untuk melihat secara lebih luas dari banyak perspektif. Konsekuensinya, kita selalu kesulitan dalam memecahkan persoalan-persoalan lingkungan yang kompleks.
Paragraf 111 kemudian mengingatkan kita bahwa persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan cepat-cepat dan pendekatan-pendekatan parsial. Manusia dengan akal budinya perlu mengendalikan teknologi dan membebaskan diri dari paradigma teknokratis. Kita mungkin perlu berani berubah lewat satu revolusi budaya. Lebih lanjut paragraf 115 membahas tentang antroposisme modern, dimana manusia memandang dirinya sebagai pusat dari alam semesta dan alam hanya sebagai objek dimana kita bisa memperlakukannya sesuka hati. Hal ini di paragraf selanjutnya kemudian dikaitkan dengan krisis ekologis dan krisis spiritual.
Bab 4: Ekologi Yang Integral
Bab empat ini mempromosikan kembali konsep ekologi integral, suatu pendekatan holistik yang menimbang dimensi-dimensi dalam kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Konsep ini dikenal benar siapapun yang menggeluti bidang lingkungan hidup atau isu-isu pembangunan berkeberlanjutan.
Paragraf 139 mengambil contoh pencemaran lingkungan untuk menggambarkan betapa perlunya konsep ekologi integral diterapkan dalam menangani pencemaran lingkungan. Isu ini memerlukan kajian tidak hanya pada ekosistem saja, tapi juga pemahaman terhadap dimensi-dimensi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Karena itu, pengendalian dan pemulihan pencemaran harus melalui pendekatan komprehensif dalam menjamin keberlangsungan hidup manusia.
Bab ini juga mengingatkan kita pada adanya kecenderungan kita untuk menyeragamkan budaya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan. Penerapan aturan dan intervensi teknis yang sama, cenderung mengabaikan kompleksitas dan lokalitas masalah yang kita tangani.
Bab keempat kemudian ditutup dengan pembahasan tentang prinsip kesejahteraan umum dan keadilan antar generasi. Dua bagian ini mengajak kita untuk berefleksi tentang sikat-sikap hidup manusia pasca-modern yang cenderung egois dan konsumtif. Pertanyaan penting dari bagian ini adalah dunia atau nilai-nilai apa yang mau kita wariskan untuk kehidupang selanjutnya?
Bab 5: Beberapa Pedoman Untuk Orientasi dan Aksi
Bab kelima dalam ensiklik ini menawar beberapa tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Salah satu yang paling penting adalah perlunya pertobatan ekologis.
Salah satu dorongan yang direkomendasikan adalah perlunya dialog dalam perumusan kebijakan-kebijakan lingkungan di tingkat lokal, nasional, dan global. Proses-proses pengambilan keputusan pun mesti transparan dan tidak hanya terfokus pada kepentingan ekonomi semata. Hal ini mencakup proses-proses penilaian dampak lingkungan dari kegiatan manusia melalui proses AMDAL (analisa mengenai dampak lingkungan) dan analisa risiko (paragraf 182 – 188).
Saran-saran yang disampaikan pada bagian itu sebenarnya bukan sesuatu yang asing atau baru bagi para praktisi dan aktor-aktor yang terlibat dalam proses-proses penilaian dampak dan analisa lingkungan. Ketika kita mendapati kondisi lingkungan krisis, pendekatan yang lebih ketat semestinya diterapkan. Tapi seringkali informasi lingkungan kita abaikan demi kepentingan manusia. Hal ini menjadi relevan dengan bab sebelumnya dimana antroposisme modern mengakari ketidakpedulian kita pada potensi kerusakan lingkungan dari keputusan kita yang keliru.
Selanjutnya, dialog politik dan ekonomi perlu menimbang pemenuhan manusia. Disini kita diingatkan bahwa perlindungan lingkungan tidak dapat ditangani dengan mekanisme pasar. Saat kita terfokus pada profit, mungkin kita mengabaikan dampak-dampak lingkungan yang akan ditanggung generasi-generasi selanjutnya. Dialog yang transparan juga perlu melibatkan agama untuk mendorong aksi-aksi perlindungan lingkungan dan kepedulian kepada kaum miskin dan kelompok marjinal yang terdampak. Mereka biasanya paling menderita akibat dampak-dampak negatif penurunan kualitas lingkungan. Pelibatan agama perlu ada menimbang “mayoritas penduduk bumi menyatakan dirinya beriman” (paragraf 201).
Bab 6: Pendidikan dan Spiritualitas Ekologis
Bagian paling penting dalam bab terakhir Ensiklik Laudato Si’ adalah seruan Paus Fransiskus untuk melakukan pertobatan ekologis, suatu perubahan cara pandang dan cara hidup kita untuk membina kembali hubungan yang harmonis dengan alam yang menunjang kebutuhan hidup kita. Hal ini merupakan pertobatan batin yang mendalam, yang melibatkan adanya pengakuan pada kekeliruan kita dalam berelasi dengan Tuhan, alam semesta, sesama manusia, dan ciptaan Tuhan lainnya. Selain pertobatan ekologis, bab ini juga mengurai perlunya perubahan gaya hidup dan perluasan cakupan pendidikan lingkungan.
Bagian paling berkesan bagi saya ada di pembahasan tentang tanda-tanda sakramental dan istirahat yang dirayakan. Bagian ini cukup memberikan permenungan yang panjang tentang makna biblis dari istirahat kontempemlatif. Mengapa Tuhan beristirahat setelah menciptakan alam semesta? Mengapa kita perlu beristirahat?
“Istirahat membuka mata kita untuk dunia yang lebih luas dan memungkinkan kita untuk mengakui hak-hak dari yang lain.” Laudato Si’ paragraf 237.
Bagian ini mengingatkan saya pada budaya-budaya konservasi seperti tutup laut yang dipraktikan beberapa kelompok masyarakat di Indonesia. Pada masa istirahat, kita mengijinkan alam berproses sehingga memberi hasil yang berlimpah kepada kita. Dalam praktik hidup kita sekarang, kita cenderung mau terus berproduksi demi pertumbuhan ekonomi dan sering mengabaikan regulasi alamiah yang berlaku di alam semesta ini.
Uraian-uraian tentang masa istirahat pun bisa kita kaitkan dengan proses-proses kajian dampak dan risiko yang selalu buru-buru kita lakukan. Kita lupa alam punya irama dan regulasinya sendiri. Kadang kita mengabaikan hal ini ketika kita memusatkan berbagai proses pada kepentingan kita.
Penutup
Secara umum, apa yang disampaikan dalam dokumen ini paralel dengan apa yang kita cari dalam penyelesaian lingkungan, seperti upaya-upaya mewujudkan harmonisasi antara irama hidup kita dan irama alam, perlunya dialog dan kolaborasi antar stakeholder, dan transparansi dalam proses-proses pengambilan keputusan.
Ensiklik Laudato Si’ adalah dokumen yang kaya. Sulit untuk tidak memuji dokumen ini. Tapi tentu tidak mudah mengimplementasi kebajikan-kebajikan yang disampaikan dalam dokumen ini. Berpihak pada kepentingan lingkungan hidup bisa sama menantangnya dengan menerapkan ajaran agama, kita butuh kerendahan hati untuk mengakui praktik hidup yang merugikan dan perlu menyangkal kenyamanan-kenyaman duniawi. Hal ini membuat kesadaran ekologis dibangun dengan ujian-ujian untuk membuat pertimbangan – pertimbangan bijak yang tidak terfokus pada diri kita sendiri.
Saya tak tahu sejauh apa Laudato Si’ telah mendorong perubahan-perubahan yang berarti. Yang pasti dokumen ini telah mencuri perhatian, dialog-dialog, dan inisiasi aksi-aksi positif untuk perawatan bumi. Dokumen ini bisa menjadi kompas moral bagi siapa saja yang mau memanfaatkannya. Dokumen ini juga memperkaya perspektif kita tentang apa yang bisa ditawar agama dalam membangun kesadaran ekologis. Hanya saja, mungkin kita perlu terus bercerita dan semakin banyak bercerita tentang kondisi bumi ini, dimensi-dimensi sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang terkait didalamnya, hikmat cerita-cerita Alkitab terkait perawatan bumi, atau esensi-esensi iman yang bisa membangun kesadaran-kesadaran ekologis.


1 thought on “Laudato Si’ : Sebuah Seruan Untuk Merawat Bumi (Review dan Refleksi Bagian 2)”